
Samino, Mister Yes! Yes, Berdikari! Foto: Kelik Broto
Begitu ingat bahwa hari ini Hari Guru, saya bersegera menulis. Sebagian besar guru berkesan bagi saya. Kesan kagum, tentu saja. Kagum akan kesederhanaan mereka, kagum tentang keteguhan hati mereka, kagum akan kebijaksanaan mereka. Beberapa sudah saya tulis di blog ini. Dan saya tak pernah bosan untuk menulis tentang mereka. Guru, inspirasi yang tak pernah kering.
Kali ini, saya ingin menulis tentang salah satu sosok guru yang fenomenal. Namanya Samino. Ia guru mata pelajaran Sejarah di SMA Kolese de Britto. Masih hidup, dan semoga panjang usia.
Samino guru yang bersahaja. Penampilannya tipikal guru-guru sekolah pedesaan yang kerap ditayangkan televisi Jakarta: berbaju batik, kadang safari, celana kain, dan bersepeda motor “CB” (Honda). Rambut ikalnya mulai menipis. Botaknya makin melebar. Selebar itu ia hadir di hati saya, juga di hati teman-teman yang pernah diajarnya.
“Isih melu uwong, Le?” Masih bekerja ikut orang, Le? Ini pertanyaan latah yang kerap ia lontarkan jika kami bertandang di rumahnya, 1 km sebelah barat Candi Prambanan, Kalasan. Jika jawabannya “ya”, ia akan menghardik, “Isih dadi batur yen ngono?” Masih jadi pesuruh!
Di matanya, kartu nama kami, dengan embel-embel jabatan supervisor, manajer, bahkan direktur, tidaklah membuatnya kagum. Pamer apa pun di depannya tiada berguna. “Lehmu entuk duit seka ngendi kuwi?” cecarnya jika kami pamer gaji atau kekayaan. Selagi masih diperoleh dengan cara bekerja sebagai karyawan, di matanya nilai kami masih 6.
Bagi Samino, profil murid yang ia kagumi adalah mereka yang berani mandiri. Wiraswasta!
Pernyataannya sangat memerahkan kuping. Seolah, berprestasi sebaik apa pun jika masih jadi karyawan tiada berartilah prestasi itu. Padahal, banyak perusahaan menjadi besar karena kerja keras para karyawannya; banyak pemilik perusahaan yang bisa ongkang-ongkang sepanjang hari tanpa risau soal hidupnya.
Saya pun teringat pelajaran Sejarah yang dibawakannya. Samino bukan guru biasa. Ia tak mengajar seperti guru-guru yang mengejar jam tayang. Teks pelajaran yang termaktub di panduan pengajaran seolah ia abaikan. Ia nyaris tak pernah mengajar sambil membuka buku pelajaran, apalagi bertindak bodoh menyuruh salah satu murid menyalin isi buku ke papan tulis. Samino mengajar lewat bercerita. Ia mengajar secara kritis. “Mbok dinalar, Le. Masa Indonesia merdeka gara-gara bambu runcing. Apa iya dengan bambu runcing para pejuang bisa ngogrok-ogrok helikopter hingga jatuh?” ujarnya suatu ketika saat membicarakan soal perlawanan 10 November di Surabaya.
Lalu?
“Indonesia merdeka karena diplomasi,” tegasnya tanpa bermaksud meremehkan arti perjuangan fisik. Samino hanya ingin meluruskan sejarah versi penguasa yang terlalu mengagung-agungkan perjuangan bersenjata, perjuangan tentara, sebagai faktor utama kemerdekaan republik. Ia mengajak kami berpikir secara cermat, dan bersikap secara kritis.
Sayangnya, dalam hal tertentu, cara mengajar yang demikian merepotkan kolega dan sekolah. Bagaimana tidak. Menurut cerita seorang guru yang pernah menjabat sebagai salah seorang direksi, nilai mata pelajaran Sejarah beberapa siswa kerap tidak tuntas karena materi yang disampaikannya di kelas berbeda atau tidak selesai. Lucunya lagi, sebagai guru generasi “mesin ketik”, Samino juga enggan naik kelas untuk sekadar belajar komputer. Alhasil, nilai siswa yang semestinya langsung dimasukkan ke program komputer, olehnya hanya diketik manual dan diserahkan ke bagian tata usaha. Ia enggan menyesuaikan zaman.
Toh begitu, saya punya kesan khusus akan sikap dalam memaknai bekerja. Menjadi karyawan, jika kemudian hanya membawa kita menjadi babu, budak suruhan, betapa hinalah kita. Ia melihat, potret karyawan pada umumnya demikian, nyaris tidak memiliki kemandirian sebagai pribadi.
“Berdikarilah!” pintanya menirukan ajakan Bung Karno, tokoh Republik yang ia kagumi. Semasa Orde Lama, Republik memiliki harga diri tinggi di tengah pergaulan internasional. Bung Karno berdiri gagah sebagai pemimpin bangsa yang berdaulat. Ia berpidato lantang sebagai pemimpin rakyat yang disegani. Bung Karno menolak campur tangan asing untuk keberlangsungan hidup negerinya. Bung Karno berprinsip, walau miskin namun punya harga diri. Ia yakin, walau miskin, rakyatnya mau bekerja. Tanpa pamrih, untuk republik.
Prinsip itu pulalah yang ia lekatkan pada semangat berwirausaha. Pada siswa yang mau berdikari, membuka usaha sendiri, ia menemukan pribadi yang berharga. Walau siswa itu miskin karena kemandiriannya, ia melihat kemegahan. Sebab, bukan soal status sosial yang menentukan posisi sosial seseorang, melainkan cara orang tersebut memperjuangkan hiduplah yang membuatnya disemati status sosial tertentu.
Menoleh ke kanan dan ke kiri, saya menjumpai kegelisahan pada diri teman-teman yang sama-sama pernah menimba ilmu dari sang guru ini. Pada mereka, tumbuh semangat berdikari yang kuat. Saat bekerja sebagai karyawan, semangat itu kerap berbenturan dengan sistem yang sudah berjalan. Beberapa memilih menyiasati benturan itu, beberapa yang lain memilih meninggalkannya untuk benar-benar berdikari, bikin usaha sendiri, menciptakan pekerjaan sendiri.
Rasanya menggetarkan melihat teman-teman berani mengambil keputusan seperti itu. Madeg dewe! Terima kasih Guru.
Selamat Hari Guru!
Jogja, 25 November 2011
AA Kunto A
[http://www.aakuntoa.wordpress.com; aakuntoa@solusiide.com]
Foto Samino pinjam dari sini.
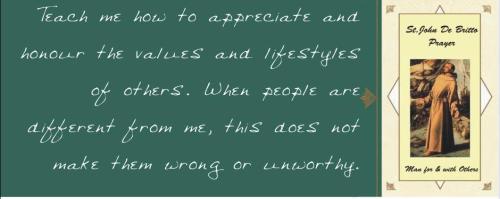


















Recent Comments